
Oleh : Bambang Budiono
blokTuban.com - Luka yang terpahat di dahi itu seperti gores kuas pelukis tua. Terbanyang, bagaimana dia, pelukis tua yang berjamban lebat dan sudut bibirnya menggantung pipa tembakau itu, penuh nafsu menggores cat minyak warna-warni pada kanvas putih.
Hari-hari asing sepanjang gang sempit, hanya ada wajah-wajah tanpa senyum. Suara laju kereta merenggut pagi hari mereka dan kunang-kunang menghempaskan mereka dalam bilik-bilik pengap tanpa jendela.
Begitu saja, hari-hari berganti. Laju kereta dan bilik pengap. Luka di dahi dan selalu tanpa senyum. Orang-orang sepanjang gang sempit tanpa nama. Embun tak menetes di sini. Matahari selalu saja ogah-ogahan untuk menerobos atap-atap semen rumah mereka.
Tak ada yang terlihat beda di sini. Dahi semua orang memliki luka gores yang sama. Langkah kaki mereka sama, baju, sepatu bahkan, bangunan dan cat rumah mereka juga sama.
Tak ada anak kecil berlarian di sepanjang gang bahakan, tak ada tangis bayi. Sepertinya anak-anak di sini lahir langsung dewasa. Berangkat bekerja, diangkut gerbong-gerbong kereta, yang lebih mirip piton bila dilihat dari ketinggian.
Wanita di sini bergerombol membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari lima sampai delapan ibu-ibu. Sampai siang mereka hanya bergerombol. Tak saling bicara. Memandang pun tidak. Sunyi. Sangat sunyi. Tak ada suara televisi, suara tawa, atau apalah yang bisa didengar telinga.
Ibu-ibu itu memakai daster dengan potongan dan warna yang sama. Warna putih kusam kombinasi hitam. Sekilas paduan warna ini terlihat menakutkan. Gaya rambut panjang terurai menambah kesan seram pada mereka.
Aku tak tahu nama gang sempit ini. Aku juga tak tahu kenapa gang semacam ini bisa ada di kota ini. Hari ketiga, sejak baling-baling besar keparat itu menjatuhkan ku di sini. Aku tak sama sekali tak tahu apa-apa tentang tempat ini. Mereka hanya menatapku dengan tatapan aneh setiap kalau aku bertanya.
Hari pertama di sini sebenarnya aku sudah ingin pergi. Ku susuri gang kecil ini seharian tapi sepertinya, gang ini tak berujung. Sampai mau pingsan aku karena haus, lapar, dan kelelahan. Ke esokan harinya, saat rombongan orang-orang dengan luka gores di dahi itu hendak pergi bekerja.
Diam-diam aku membuntuti mereka dari belakang. Pelan, aku mengendap agar tak ketahuan. Bersembunyi di balik tiang listrik, di balik pagar rumah bahkan tong sampah. Lama aku mengikuti mereka.
Sampai pegal kakiku. Tapi sepertinya, jarak yang mereka tempuh untuk sampai ke stasiun kereta tak masuk akal. Untuk suara laju kereta yang bisa terdengar dari dalam gang, harusnya jaraknya tak sejauh ini.
Sesaat kemudian terdengar suara laju kereta mendekat. Lega rasanya hatiku, sebab kakiku sepertinya tak sanggup lagi berjalan. Semakin dekat suara laju kereta, terdengar pula olehku suara rem menggesek keras rel, pertanda kereta akan berhenti, pikirku.
Benar saja, sejurus kemudian tak terdengar lagi olehku suara laju dan rem itu. Aku bergegas masuk barisan setelah membuat tanda di dahiku menyerupai luka gores orang-orang itu. Merangsek aku ke depan, membelah orang-orang berbaris dengan wajah-wajah dingin itu.
Sampai di baris terdepan aku kaget dan bingung luar biasa. Tak ada stasiun di depan, tak ada kereta, tak ada gerbong dan tak ada apapun.
Dalam bingung dan tanya, ku beranikan menoleh kerah kerumunan orang-orang dengan luka di dahi. Ekspresi wajah mereka masih sama seperti sebelumnya. Dingin dan kaku.
Berjam-jam aku berjalan mengikuti mereka, mengendap seperti maling, bersembunyi dengan dada ngap-ngapan takut ketahuan. Ternyata, aku tak pernah sampai kemana-mana.
Yang di tuju oleh orang-orang dengan luka di dahi ini adalah gapura pintu masuk gang sempit. Tempat tinggal mereka dan tempat aku terlantar tiga hari ini. (*)
Temukan konten Berita Tuban menarik lainnya di GOOGLE NEWS





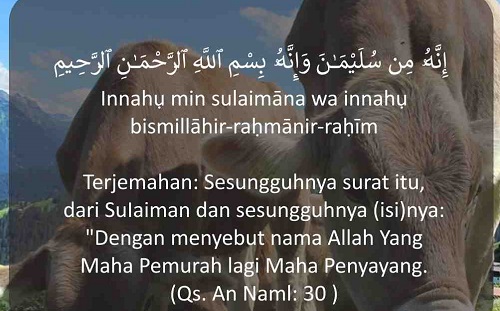


.jpg)








0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published