
Karya: Ika Nurul Habibah
Angin telah menggelepar, sunyi meruah tanpa menerka, pucuk dahan Ketika malam telah rebahkan jubah hitamnya, aku selalu siap menanti kedangan suami tercinta dengan wajah sumringah dan aneka masakan kesukaanya agar lelahnya usai bekerja tersibak oleh sambutanku. Ketika jam dinding telah menunjukkan pukul 21.00 WIB dan ia sebelumnya tidak memberikan kabar akan pulang terlambat, maka gundah akan menyelubung takut terjadi sesuatu padanya. Ketika langkah kakinya memasuki pintu depan, kusambut ia dengan senyum simpul sambil kubawakan tas kerjanya. Ia selalu menyapa hangat atas apa yang aku lakukan dan mencium kening adalah kebiasaan yang tak bisa tertinggal.
Sikap lembut dan senyum manis yang menunjukkan lesung pipitnya selalu menjadi hal paling mendamaikan. Ia sangat menghargai apapun yang aku lakukan untuknya. Pernah ia pulang kerja dengan perut kenyang karena ada teman sekantornya yang syukuran, sedangkan di meja makan telah siap beragam masakanku untuknya, dengan penuh cinta ia kembali makan malam hingga perutnya begah meskipun aku sudah melarangnya.
“Sudahlah Mas, tidak apa-apa, biar masakannya adik simpan. Nanti Mas kekenyangan” Ujarku melarangnya.
“Tidak apa-apa dindaku sayang, masakan ini dibuat dengan penuh cinta” Ujarnya merayu.
Demi membuatku senang, makanan itu ia lahap habis. Semua itu semakin membuat aku jatuh cinta padanya, bukan karena lesung pipit atau wajah manisnya saja, tapi sikap tanggung jawab, perhatiannya padaku, ketulusan hati, dan kelembutannya selalu membuat aku terkesima.Ia selalu bersikap bijak, bagiku ia adalah imam terbaik yang dipilih Tuhan untukku. Lelaki tangguh yang siap membawaku pada mahligai rumah tangga yang bahagia. Kadang ia bersikap manja, merajuk makan agar aku menyuapinya, tapi aku tahu yang ia lakukan hanya untuk menunjukkan rasa cintanya padaku, agar perhatianku tak lepas dari pandangannya. Suamiku memang selalu memiliki cara untuk membuatku menyunggingkan senyuman.
Semua itu selalu menjadi masa-masa menyenangkan dalam pernikahan kami.Tapi masa tak pernah berhenti meski sedetikpun, yang terjadi kini adalah kebalikan dari kesenangan yang pernah kami lewati bersama.Akhir-akhir ini waktu laksana memasung lesung pipit suamiku hingga tak lagi tampak.Senyumnya bagai ikut luruh oleh derasnya hujan malam ini. Aku bahkan rindu tatapan matanya yang penuh cinta, dekapannya yang selalu menenangkan, dukungannya nan bijak atau panggilan dinda yang membuatku tersipu malu.
Wajah lelah suamiku selalu menjadi pemandangan setiap ia pulang dari kantor. Tak ada sapaan hangat seperti dulu, bahkan kecupan kening yang selalu menjadi rutinitas setiap berangkat dan pulang bekerja. Aku mencoba berdamai, mungkin ia memang sangat lelah setelah bekerja seharian di kantor atau aku telah berbuat salah yang membuatnya kecewa? Entahlah, aku menjadi semakin gundah. Aku lebih memilih diam dan mengalah, ketika suasana telah tenang aku akan menanyakan perihal yang membuat aku seperti terhunus sembilu.
“Mas, bicaralah. Apa adik sudah membuat kesalahan pada Mas?.Kalau memang benar demikian, mengapa Mas tidak menegurnya, mengapa Mas tidak mengingatkan adik.Tapi adik mohon jangan diamkan adik seperti ini.Apa yang harus adik lakukan untuk membuat Mas tersenyum kembali? Katakanlah Mas” tuturku parau dengan deraian air mata.
Tiada jawaban, hanya angin yang menjawab kebisuan ini, bahkan suara jangkring di luar rumah terdengar lebih nyaring dari biasanya, karena kami hanya membisu, bukan karena tak bisa bicara tapi rasa enggan yang memasung kata.
Resah di hati mulai menggunung.Kubicarakan perubahan sikap suamiku malam itu dengan nada selembut mungkin.Aku memintanya untuk makan malam, sebab pagi tadi tak sempat berharap.Laksana terhunus panah yang paling tajam, aku terbelalak, ajakanku disambut dengan kemarahan dan suara lantang sambil mengibaskan tanganku dengan kasar.
“Sudah kukatakan, aku tak ingin makan malam bersamamu, apa kamu tuli!Hahh, jangan ganggu aku”.
Air mata yang jatuh sederas hujan di luar, jangankan menjawab pertanyaanku tentang perubahan sikapnya, sambutan baik akan ajakanku untuk makan pun tak kuperoeh. Duhai suamiku tercinta ada apakah denganmu.Mengapa sedemikian kasar engkau sekarang.Sikap lembutnya yang dulu selalu mewarnai hari-hari kami seperti terbawa angina, menggelepar entah ke mana.Caranya bicara bahkan lebih bayak membentak.Bentakan, jangankan dulu membentakku, menyuruhku pun selalu dengan kata tolong.Ke manakah sosok suamiku yang dulu, aku bahkan kadang merasa takut dengan kemarahan dan sikap kasarnya.
Aku tak mau menyerah begitu saja, wajah manis suamiku mulai menjadi wajah yang sangat menakutkan untuk kutatap ketika ia telah terjaga. Bahkan lesung pipitnya yang selalu menjadi menjadi pemandangan yang mempesona di mataku kini nyaris tak pernah tampak lagi. Aku berusaha keras mencari tahu pada rekan-rekannya, akhirnya kuketahui bahwa investasi uang perusahaannya pada suatu bank telah lenyap karena masalah tertentu pada pihak bank, yang menyebabkan suamiku kehilangan rasa percaya dirinya sebagai seorang lelaki yang kini berpenghasilan lebih minim dibanding aku yang berprofesi sebagai dosen yang telah sertifikasi dan penulis fiksi.
Materi memang dibutuhkan untuk bertahan hidup.Tapi itu bukanlah jaminan untuk bahagia. Aku masih sangat menghormatinya, meski karirku lebih melejit darinya, bagiku ia tetap lelaki paling hebat yang pernah kutemui. Aku bisa berkarir juga dengan izin, dukungan, dan bantuannya. Semua kesuksesan ini bukanlah apa-apa dibandingkan dengan bahagianya memiliki suami sebaik dia. Tapi haruskah ia sekarang menjadi sosok yang lain. Mas Wahyu, jadilah dirimu sendiri.Hari-hari penuh tawa kini entah terasa lebih suram, bahkan membuat aku lebih banyak mematung memandangi foto-foto kami.
Aku tak pernah lelah menghiburnya. Aku sangat mengerti alasan suamiku menyembunyikan masalah ini sebelumnya karena ia tak ingin aku terbebani oleh masalah yang tengah ia hadapi. Aku tahu ia sangat mencintaiku, dan mendampinginya ketika ia sedang terjatuh adalah kewajibanku sebagai seorang istri. Tapi setiap kalimat manis yang kuutarakan justru membuatnya semakin marah, terkadang aku merasa malu ketika Diman, supir kami memergoki pertengkarang kami.
“Mas, bagi adik, Mas adalah lelaki paling hebat Mas, tetap seperti dulu. Materi bukanlah jaminan bahagia Mas. Kita hidup memang butuh uang, tapi untuk hidup bahagia adik lebih membutuhkan Mas” ucapku lembut.
“Alahh, kau pikir aku percaya omong kosongmu, kamu kira aku tidak tahu kalau kamu mau mengejekku.Menunjukkan pada teman-temanmu kalau kamu itu lebih berhasil dari suamimu”.
“Mas, sungguh!Adik tidak pernah punya pikiran seperti itu”.
“Diam! Aku tidak mau dengar celotehanmu yang tak berguna itu!”.
Selalu demikian, bila aku coba meyakinkannya.Aku bahkan tak pernah berpikir untuk merendahkan suamiku.Aku sangat mengerti, dia adalah lelaki yang wajib kuhormati selama hidupku.Aku sungguh malu pada Diman.Bukan sekali dua kami dia mengetahui pertengkarang kami, namun hampir setiap hari.
Ketika novel baruku akan terbit, aku membagi rasa bahagia itu, namun yang kuperoleh adalah kemarahannya. Bahkan ketika ku dekap lembut tangannya karena ingin mengajaknya hadir dalam salah satu undangan, ia mendorong tubuhku hingga kepalaku terjorok oleh sudut meja yang lancip.
“Kehadiran Mas, adalah hal paling istimewa”
“Kamu ingin aku datang biar kamu bisa pamer kalau kamu itu hebat,iyaa. Aku tidak sudi”
Tiada kepedulian walau melihatku berdarah dengan deraian air mata.Hingga Diman datang tergopoh-gopoh membawa obat merah dan perban untuk membantuku.
Luka di kepala membuatku terpaksa tak hadir juga dalam undangan teman kerjaku.Tapi luka ini tak seberapa, lebih sakit luka di hati yang merambah seluruh persedian.Aku sungguh kecewa, mengapa tega sekali suamiku berbuat ini, bahkan meninggalkanku disaat aku sedang terluka.Lihatlah, yang seharusnya mengobatiku bahkan pergi begitu saja, menyisakan seorang Diman.
“Sudah buk, jangan menangis” ucap Diman, menyodorkan tisu
Suamiku yang selalu tersenyum manis dengan kedua lesung pipitnya kini menjadi begitu muram. Rambutnya yang sedikit ikal dan selalu disisir rapi kini Nampak lebih berantakan.Kulit sawo matangnya yang selalu kuusap lotion kini bahkan jarang kusentuh, yang ada hanya tangan lembutnya yang dulu selalu membelai kepalaku dengan penuh kasih berganti tamparan dan kekerasan yang kerap kali terjadi di ujung kemarannya.
Setiap malam dalam kesunyian yang ada, aku kerap kali menangis, memandangi foto pernikahan kami dulu.Lihatlah, betapa bahagia wajah dalam foto itu. Wajah manis dengan lesung pipit yang sempurna terlihat di kedua pipinya, merangkul wanita sederhana di sebelahnya yang menggunakan kebaya putih dan cincin bertuliskan nama suaminya. Menunggunya berjam-jam dari balik jendela kamar. Menyambutnya pulang meski yang kuterima hanya kemarahannya.Melepaskan kedua sepatunya dengan penuh rasa cinta, meski istana cinta yang kami bangun hampir sempurna runtuh.
Rasa sepi dan kerinduan yang membekam membuat aku lebih banyak diam dan murung. Diman yang hampir setiap hari menjadi saksi pertengkaran kami, mulai bersahabat dengan kemurunganku.Ia sungguh padai mengusir rasa sedihku dengan humor-humornya yang membuat aku melukis tawa dibalik hati yang luka. Diman menjadi teman yang cukup menyenangkan.Aku mulai nyaman berbicara dengannya, membagi dukaku, membicarakan novel-novel yang kutulis, tertawa bersama, dan banyak hal yang membuat aku merasa ingin tersenyum dan bangun dari luka-luka yang membelenggu.
Simpati Diman semakin hari membuat aku semakin luluh.Kalimatnya yang menghibur dan menentramkan membuat aku merasa lebih baik dan hari-hariku kembali berwarna karenanya.Setiap luka yang dihasilkan tangan besi suamiku, selalu dijamah oleh tangan sutera Diman dengan kasih sayangnya. Rasa rindu akan perhatian suamiku kini terobati oleh sosok Diman, supir kami.
Aku merasa semakin nyaman dengan sikap perhatian Diman.Ia yang dulu selalu memangilku dengan sebutan Bu Vony, kini bahkan kuminta untuk memanggilnya dengan nama saja tanpa sebutan ‘bu’. Seorang Diman yang kurus ceking, dengan kulit sawo matang tanpa lesung pipit memang berbeda dengan sosok suamiku yang tinggi tegap dengan rahang kukuh dan wajah manisnya, namun sikap Diman yang lembut ditambah perhatiannya yang tiada lapuk membuat sosok suamiku yang manis dan bertangan besi mulai terkikis.
Diman, supir kami. Aku bahkan tak pernah membayangkan akan begitu dekat dengannya. Bahkan sosok sederhana itu yang membuat aku semangat menjalani hari-hariku yang sebelumnya kelabu. Aku juga merasa senang memasak untuknya. Apapun yang aku masak, di matanya selalu ada binar bahagia setiap kali menerimanya dan akan langsung melahapnya habis tanpa menyisakan sebutir nasipun. Terlebih ia yang selalu mengantarku ke tempat manapun, menyisakan banyak waktu bagi kami untuk selalu bersama dan bepergian ke tempat-tempat yang kami inginkan. Kursi mobil di belakangpun sekarang kosong karena aku selalu duduk di depan, bersebelahan dengan Diman, menikmati desir angin yang berdesir lembut dengan iringan musik romantis, sungguh syahdu hari-hari yang kami lalui bersama.
Aku dan Diman rebah di kamar utama. Siang ini memang lebih terik dari biasanya. Setelah lelah bepergian bersama, aku dan Diman memutuskan untuk beristirahat bersama di kamar untuk mengusir lelah yang telah bergelayut. Tanpa terduga tiba-tiba suamiku datang dan membuka pintu kamar kami yang tidak terkunci dan mendapati aku dan Diman yang sedang istirahat bersama. Dengan wajah merah padam ia mengambil pistol di laci mejanya dan tanpa hitungan detik langsung menarik pelatuk pistol hingga melemparkan dua peluru ke dada Diman dan satu peluru tepat di jantungku. Darah segar mengucur hebat, tangan Diman mendekat tanganku yang berlumur darah. Memandang mataku yang mulai sayu dan dengan senyum yang dipaksakan Diman akhirnya memejamkan matanya. Mata yang pernah memberiku arti sebuah perhatian, mata yang tak kan pernah terbuka kembali meski satu kalipun, mata yang akan terpejam selamanya.
Aku dan Diman kini hanyalah sebuah nama, nama yang akan tertulis di batu nisan. Aku mengerti yang terjadi bukanlah kehendakku ataupun kehendak suamiku, bahkan tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Semarah apapun suamiku, ia sangat mencintaiku dan tak berkenan ada lelaki lain yang menjamah hatiku, namun sikap kasarnya telah membuat wajah manisnya tersisih oleh sosok Diman yang sederhana dan penuh perhatian.Tangan besinya juga telah menjadikan alur rumah tangga kami tak berjalan seperti harapan yang pernah kami utarakan bersama. Matanya kini yang sempurna melukiskan penyesalan,mendekap erat tubuhku yang sudah tak bernyawa, mencium keningku yang mulai dingin, membelai rambut panjang hitam legamku yang berhiaskan darah segar, menggoyangkan berkali-kali tubuh lemasku, menepuk bahuku berulang-ulangsambil memohon agar aku membuka mata, lantas dengan deraian air mata, suamiku tercinta bergumam lirih “Dinda, maafkan aku. Aku mencintaimu”.
*Ika Nurul Habibah, Gadis manis kelahiran Brondong, Lamongan. Saat ini menjadi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kini sedang berproses kreatif di Komunitas Sanggar Sastra (Kostra) Unirow Tuban.
Foto Ilustrasi: www.merdeka.com











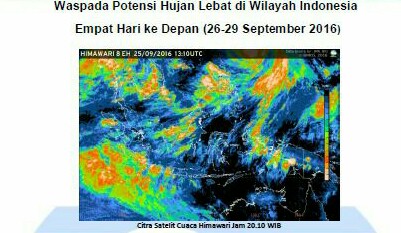





0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published