
Oleh: Nanang Fahrudin
Dulu, ketika media hanyalah cetak, radio dan segelintir televisi, masyarakat tak cepat panik oleh sesuatu yang heboh di media. Maklum, jumlah pembaca media hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk Indonesia. Sebagian lain, terutama yang tidak mengonsumsi media, mendapatkan informasi dari warung, gardu, pasar, atau jamaah jamaah pengajian. Sebuah informasi mengalir pelan, tidak tergesa gesa.
Meski tidak tergesa gesa, bukan berarti taka da masalah. Karena informasi yang menyebar diatur oleh penguasa. Pembredelan dilakukan pemerintah bagi media yang nekat memberi informasi yang berlawanan dengan apa yang diinginkan penguasa. Itulah media masa orde baru.
Meski demikian, perdebatan akan “kebenaran informasi” sering dilakukan oleh orang orang tertentu saja yang punya jangkauan ke media. Maklum, tak semua orang bisa tersambung dengan media. Tak semua semua orang bisa ngomong di media massa. Penggiringan opini pun berjalan lambat.
Tapi, teknologi terus berkembang. Tahun 2000 an media online bermunculan. Ketika sebelumnya masyarakat harus berlangganan koran, menonton televisi, atau mendengar siaran berita di radio, pada era ini siapapun bisa mengakses informasi yang disajikan oleh media online dengan sangat cepat. Informasi menyebar semakin cepat dan tanpa batas. Media online berperan memberi informasi dengan cepat, namun juga mengundang konflik paling cepat juga. Media online memproduksi informasi dengan cepat, dan pembaca menanggapinya dengan cepat juga. Media dan pembaca sama sama jarang melakukan pengendapan terlebih dahulu.
Lalu, muncul media sosial macam Facebook dan semacamnya yang benar benar mengubah dunia informasi. Media sosial menjadi “media massa” milik semua orang. Dunia jurnalistik menemukan tantangannya, karena informasi tak hanya dimonopoli oleh media massa yang notabene milik sebuah perusahaan, yang diorganisasi dengan struktur ketat, pembagian tugas jelas, dan ada tanggungjawab sebagaimana amanat UU Pers.
Semua orang kini berperan menjadi penyedia informasi. Mereka bisa seorang diri atau berkelompok, lalu memproduksi informasi dan menyebarkannya ke publik. Seringkali mereka cukup copy paste sebuah informasi yang dishare lewat media soosial. Jadilah informasi bagaikan hujan yang terus turun dengan deras. Banjir informasi pun tak terelakkan. Membedakan mana informasi yang diolah oleh perusahaan pers atau diolah oleh perseorangan atau kelompok orang sudah sulit dilakukan. Parahnya semua mengaku berpijak pada kebenaran.
Antara media massa professional atau “media massa” perorangan tak lagi dilihat dari seberapa taat mereka pada etika jurnalistik atau kaidah kaidah jurnalistik. Mereka hanya membutuhkan seberapa besar share nya, atau seberapa banyak viewer nya. Mempertanyakan apa itu jurnalisme? Seperti berteriak di dalam air. Apalagi sampai bertanya tentang sembilan elemen jurnalisme sebagaimana diungkap Bill Kovvach dalam bukunya.
Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk berebut pengaruh. Kelompok kelompok yang berbeda membuat website sendiri, membuat rubrik sendiri, memposting berita berita yang hanya segaris dengan pandangannya saja. Ketika ada sebuah website mengunggah sebuah informasi yang menyerang kelompok tertentu, maka link berita itu akan cepat disebarkan lewat media sosial oleh orang orang yang tidak suka dengan kelompok tertentu itu. Begitupun sebaliknya.
Informasi yang diproduksi untuk kepentingan kelompok tertentu itu, kemudian menjadi informasi tak bertuan yang siapapun bisa “menggorengnya”, menjadi informasi lain sama sekali, dengan judul berbeda, yang kemudian di posting oleh website lainnya. Informasi berupa link website hasil gorengan itu kemudian dishare lagi dan lagi. Belum selesai tahap itu, informasi didesain dengan visual simple yakni berupa meme meme yang juga dishare lewat media sosial; Facebook, Twitter, dan medsos lain.
Salah satu contoh adalah kasus kematian Siyono yang diduga teroris oleh Densus 88. Informasi tentang Siyono mudah menyebar. Sebagai masyarakat awam, kita sudah tidak tahu lagi mana fakta yang benar tentang kasus itu. Berita beragam diunggah oleh website kelompok ataupun website profesional. Bahkan, berita kemudian melebar seakan akan Muhammadiyah pro Siyono, dan NU pro Densus 88. Siapa awal penyebar isu itu? Tak ada yang tahu. Dan informasi itupun menggelinding lewat meme meme tentang Siyono, tentang NU, tentang Muhammadiyah.
Siapa yang beruntung dengan isu itu? Saya bukan hendak mendiskusikan Siyono. Namun, kasus ini saya ambil sebagai contoh untuk sengkarutnya dunia informasi saat ini. Menguji kebenaran dalam setiap berita sudah jarang dilakukan. Semua menjadi serba cepat. Ada link berita di Faceebok, lalu kita merasa cocok dengan sikap kita, buru buru kita share, dan terkadang tanpa kita baca sampai tuntas terlebih dulu. Pokoknya baca judulnya, share, dan komen.
Inilah dunia informasi saat ini. Kita, tanpa sadar, adalah media media yang ikut menyebarkan informasi melalui jejaring media sosial. Kita tanpa sadar ikut menyebar konflik konflik yang sengaja dibangun oleh pihak tertentu. Kita ternyata adalah tangan tangan yang digerakkan untuk membenci seseorang, mengajak orang lain untuk menjadi pengikut pandangan kita. Kita adalah media media yang merusak diri kita.
Oleh karena itu, akan sangat bijak jika kita menjadi masyarakat internet yang cerdas. Kita mengaku sebagai kelompok yang memegang bahwa Islam rahmatan lil ‘alamin, namun setiap hari kita menyebar link link website yang berisi informasi informasi menyesatkan, menebar kebencian, menyudutkan kelompok lain, menganggap kelompoknya paling benar, dan lain sebagainya. Terkadang, kita tidak mengenal diri kita sendiri.
Tulisan ini bukan berpretensi untuk berkampanye stop share link website yang tidak jelas, namun hanya ingin berkata bahwa informasi yang menyebar di internet melalui medsos tak semuanya perlu kita share. Tak semua informasi mengandung kebenaran. Jangan sampai kita malah menjadi pembunuh bagi masa depan kita sendiri. Salam.















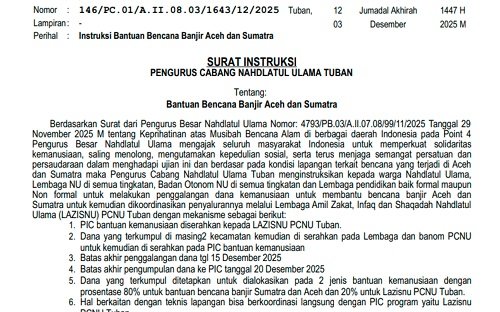
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published