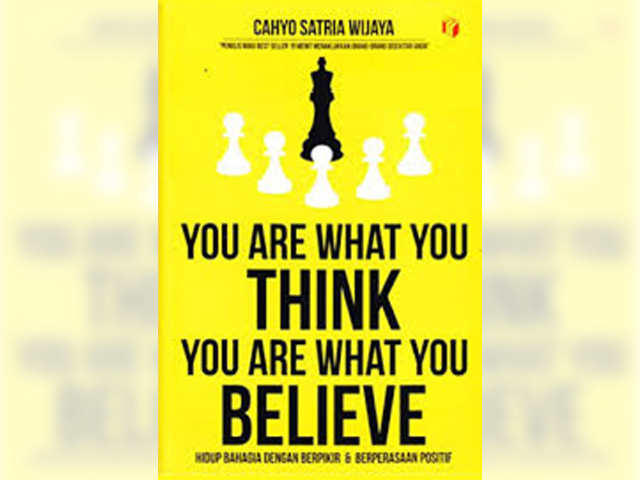Oleh: Ichwan Arifin*
Tanpa wanita takkan ada bangsa manusia. Tanpa bangsa manusia takkan ada yang memuji kebesaranMu. Semua puji-pujian untukMu dimungkinkan hanya oleh titik darah, keringat dan erangan kesakitan wanita yang sobek bagian badannya karena melahirkan kehidupan (Pramoedya Ananta Toer, Jejak Langkah). Kutipan Pramoedya tersebut meneguhkan kemuliaan perempuan dalam aspek fundamental kemanusiaan dan peradaban, yaitu ibu dari kehidupan.
Dalam sisi itu, Pram tidak sendiri. Ada banyak tokoh terkemuka menyebut keagungan dan kemuliaan perempuan. Misalnya Soekarno, pandangan progresifnya tentang perempuan dituangkan dalam “Sarinah”. Interaksi masa kecil dengan Sarinah, pembantu keluarga, ikut mewarnai perkembangan pemikiran proklamator, tidak hanya pandangannya tentang perempuan, tapi juga kemanusiaan.
Di balik itu, sejarah punya narasi berbeda dan kontradiktif. Tetralogi Pulau Buru, meskipun fiksi, namun merefleksikan gambaran ketertindasan perempuan pada masa kolonial. Karakter Nyai Ontosoroh adalah simbol pergulatan perempuan dalam menegakkan hak dan harga diri, serta perlawanan terhadap tata sosial yang tidak adil. Titik darah, keringat dan erangan itu tidak berhenti selepas melahirkan generasi baru. Namun harus terus berlanjut untuk melawan ketidakadilan yang melingkupi hidupnya. Situasi itu dihadapi perempuan sejak zaman kolonial sampai millenial, tentu dalam skala dan isu yang berbeda.
Hal itu juga bukan masalah yang hanya dihadapi perempuan Indonesia, namun di seluruh dunia. Karena itu, Hari Perempuan Internasional 8 Maret, sepatutnya dijadikan momentum refleksi dan aksi nyata terkait dengan pergerakan perempuan, bukan melalui seremoni dan kegiatan yang banal.
Menyebut Hari Perempuan Internasional tidak dapat dilepaskan dari nama Clara Zetkin (1857-1933), feminis dan aktivis Partai Sosialis Demokrat Jerman. Pada 1910, Zetkin mencetuskan ide perlunya memiliki momentum hari perempuan secara internasional. Di Indonesia, nama Clara Zetkin disebut Soekarno sebagai ibu revolusi. Muncul juga di “Sarinah” dan beberapa pidato Soekarno. Namun, sejak Orba, nama Clara Zetkin tidak banyak disebut. Mungkin kelekatannya dengan ideologi kiri menyebabkan pemikiran dan kontribusinya dalam pergerakan perempuan tidak dijadikan rujukan, bahkan cenderung ditutupi.
Saat ini, meski banyak kemajuan dan kondisi yang jauh lebih baik dalam kehidupan perempuan, namun tantangan dan problem yang dihadapi masih relatif sama. Terutama dialami perempuan kelas bawah; Pertama, kekerasan terhadap perempuan dan human trafficking. Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, pada 2017 jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani mencapai 259.150 kasus.
Kasus paling tinggi adalah kekerasan dalam ranah personal seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan masa pacaran, terhadap anak perempuan, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan kasus perdagangan manusia, menurut Kabagpenum Polri Kombes Martinus sebagaimana dikutip Republika, pada 2017 jumlahnya mencapai 194 orang dengan korban terbanyak perempuan (120), anak-anak (55) dan laki-laki (21). Kasus terbaru, kematian Adelina Sau, Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia pada 11 Februari 2018 karena perlakuan tidak berperikemanusiaan majikannya merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat dikategorikan human trafficking.
Ke dua, metamorphosis bentuk kekerasan. Kemajuan teknologi komunikasi berkontribusi terjadinya perubahan bentuk tersebut. Penggunaan teknologi dan cyber media, misalnya prostitusi dibawah umur online, bullying, dan sebagainya.
Ke tiga, artefak domestifikasi peran perempuan warisan Orba. Julia Suryakusuma menyebutnya sebagai ideologi ibuisme negara, dimana negara mengkonstruksi perempuan dan “memenjarakannya” dalam ranah domestik. Mengubahnya tidak mudah, karena domestifikasi dilakukan secara sistematis dan kurun waktu lama.
Saat Orba tumbang, reformasi mendorong perubahan melalui kebijakan publik “ramah perempuan”. Buahnya, peluang perempuan beraktifitas di sektor publik terbuka lebar. Namun, belum sepenuhnya optimal. Kendala juga terletak pada perempuan sendiri, seperti pemahaman gender yang tidak sejalan dengan kesetaraan perempuan dipahaminya sebagai kodrat. Contoh lainnya, affirmative action ranah politik juga belum maksimal jika hasilnya diukur dengan ukuran kuantitas dan kualitas perempuan yang ada di lembaga politik seperti legislatif dan sebagainya.
Ke empat, struktur dan kultur sosial yang belum ramah perempuan. Budaya politik patriarkhi dan tafsir sepihak terhadap agama sebagaimana dikemukakan Kathryn Robinson dalam Religion, Gender and the State in Indonesia, berkontribusi terjadinya represi dan kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya dilakukan kelompok masyarakat tapi juga negara. Robinson, mengutip data Human Right Watch 2015 menyebutkan 279 regulasi lokal (misalnya dengan nuansa agama tertentu) yang mendiskriminasi perempuan.
Karena itu, Hari Perempuan Internasional menjadi momentum penegasan bahwa perjuangan belum selesai. Soal itu juga bukan problem perempuan semata, tapi menyentuh wajah kemanusiaan dan peradaban. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran diri dan menjadikannya sebagai gerakan kemanusiaan. Panggilan sejarah buat kita semua untuk melakukan perubahan. Sebagaimana dikemukakan Pramoedya, bangsa yang dengan mudah menanggalkan perikemanusiaan dengan sendirinya mudah pula tersasar dalam perkembangan sejarah.
*Penulis adalah Ketua Gerakan Kibar Indonesia, Alumnus Pasca Sarjana UNDIP Semarang.